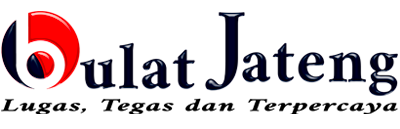bulat.co.id - Instruksi razia terhadap kendaraan berpelat nomor Aceh yang terjadi di wilayah Sumatera Utara atas arahan Penjabat Gubernur Bobby Nasution (selanjutnya disebut Bobby) telah menimbulkan polemik di ruang publik. Tindakan ini mendapat sorotan tajam, tidak hanya dari masyarakat sipil tetapi juga dari anggota legislatif. Pertanyaannya kemudian adalah apakah tindakan dimaksud dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam hukum positif Indonesia? Jika iya, pasal apa yang relevan digunakan? Opini ini mencoba menjawab pertanyaan tersebut secara sistematis melalui pendekatan normatif dan teori hukum pidana yang berlaku.
Dalam kerangka negara hukum (rechsstaat), setiap tindakan pejabat publik harus memiliki dasar hukum (legal basis). Tanpa dasar tersebut, setiap bentuk penggunaan kekuasaan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, baik secara administratif maupun pidana. Pasal 1 ayat (1) KUHP mengatur asas legalitas (nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali) yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang telah ada sebelumnya.
Instruksi razia terhadap kendaraan berdasarkan pelat nomor daerah tanpa adanya aturan hukum yang jelas dan tertulis berpotensi melanggar prinsip ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah Gubernur memiliki kewenangan memerintahkan razia kendaraan lintas provinsi hanya berdasarkan pelat nomor? Jika jawabannya tidak, maka perintah tersebut dapat dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang dapat berimplikasi pidana.
Potensi Delik: Pasal 421 dan Pasal 333 KUHP
Pasal 421 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) merupakan ketentuan yang mengatur mengenai penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara. Rumusan pasalnya menyatakan, "Seorang pejabat yang dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dihukum dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan." Norma ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan koersif yang dilakukan oleh pejabat publik yang bertindak di luar batas kewenangannya.
Secara teoritik, pasal ini merupakan bentuk dari ambtelijke delicten atau delik jabatan, yakni tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh subjek tertentu, yaitu pejabat yang menyalahgunakan kewenangan jabatannya. Dalam konteks hukum pidana modern, hal ini sejalan dengan pandangan Pompe dan Hazewinkel-Suringa yang menekankan bahwa kejahatan jabatan merupakan pelanggaran terhadap kepercayaan publik yang mana kekuasaan yang seharusnya dijalankan untuk melindungi justru digunakan untuk menindas.
Apabila dalam kasus tertentu seorang pejabat seperti Penjabat Gubernur menginstruksikan razia terhadap kendaraan berpelat nomor Aceh tanpa dasar hukum yang eksplisit, baik dalam bentuk peraturan daerah, peraturan gubernur, maupun regulasi nasional terkait lalu lintas, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Lebih jauh, apabila razia tersebut tidak bersifat umum, melainkan secara selektif menargetkan kendaraan dengan pelat tertentu dan menyebabkan warga dipaksa berhenti, menunjukkan dokumen yang sebenarnya tidak wajib, atau mengalami perlakuan diskriminatif hanya karena identitas plat nomor daerah, maka telah terjadi unsur pemaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 KUHP.
Dalam perspektif teori diferensiasi wewenang, kekuasaan administratif memiliki batas legalitas yang ketat. Wewenang yang dijalankan tanpa dasar hukum yang sah bukan saja tidak sah secara administratif, tetapi juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila berdampak pada pelanggaran hak-hak warga negara. Tindakan tersebut melanggar prinsip legalitas kekuasaan eksekutif, sebagaimana dirumuskan dalam asas 'tidak ada kewenangan tanpa dasar hukum" (geen bevoegdheid zonder wet).
Dengan demikian, pemanfaatan jabatan publik untuk menginstruksikan tindakan yang membatasi kebebasan warga tanpa landasan normatif yang sah tidak dapat dibenarkan secara hukum. Dalam kerangka negara hukum (rechtstaat), setiap tindakan kekuasaan harus dapat diuji legalitasnya. Ketika kekuasaan dijalankan secara menyimpang, maka hukum pidana hadir sebagai ultimum remedium untuk menegakkan batas dan akuntabilitas kekuasaan itu sendiri.
Selanjutnya Pasal 333 KUHP menyatakan, "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan orang lain, atau terus-menerus menghilangkan kemerdekaan itu, dihukum penjara paling lama delapan tahun." Unsur delik ini meliputi:
a. Perbuatan dilakukan secara sengaja;
b. Perbuatan dilakukan melawan hukum;
c. Terdapat penghilangan kemerdekaan seseorang.
Perampasan kemerdekaan dalam konteks hukum pidana dapat dimanifestasikan dalam berbagai bentuk tindakan, seperti penahanan tanpa dasar hukum yang sah, penculikan, penyanderaan, dan bentuk pembatasan kebebasan lainnya. Dalam yurisprudensi Hoge Raad tertanggal 9 April 1900 (W.7427), ditegaskan bahwa seseorang yang dikurung dalam suatu ruang dan kemudian berhasil melarikan diri melalui jalur yang tidak disediakan secara resmi tanpa menggunakan kekerasan maupun mengalami kekerasan telah mengalami perampasan atas kemerdekaannya.
Kemerdekaan yang dimaksud di sini secara spesifik merujuk pada kemerdekaan bergerak (freedom of movement) sebagaimana dipertegas dalam putusan Hoge Raad tanggal 3 Januari 1921. Pembatasan terhadap kebebasan bergerak tidak semata-mata dimaknai secara fisik, seperti pengurungan atau penahanan secara langsung, tetapi dapat pula berupa paksaan psikologis yang cukup kuat untuk menghambat pergerakan seseorang.
Selain itu, pengertian "ruangan" dalam konteks rumusan delik perampasan kemerdekaan sebagaimana termuat dalam Pasal 333 KUHP harus dimaknai secara luas. Interpretasi ini tidak terbatas pada ruang tertutup secara konvensional, melainkan mencakup juga alat transportasi, seperti kendaraan bermotor (mobil) yang dapat berfungsi sebagai sarana pembatasan kebebasan apabila seseorang ditahan atau dikurung di dalamnya secara melawan hukum.
Sehingga apabila razia tersebut mengakibatkan warga Aceh kehilangan haknya untuk bergerak secara bebas di wilayah negara kesatuan RI atau terjadi bentuk pembatasan mobilitas secara paksa tanpa dasar hukum yang jelas, maka unsur delik dalam Pasal 333 KUHP dapat diduga terpenuhi. Apalagi jika disertai tindakan penggeledahan atau pemeriksaan yang intimidatif, maka hal itu tak hanya melanggar UU Lalu Lintas, tetapi juga menyentuh ranah pidana karena menyentuh hak kemerdekaan individu.
Bertentangan dengan Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Berdasarkan tindakan penggeledahan atau pemeriksaan kendaraan bermotor harus dilakukan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) serta Peraturan Kepolisian yang relevan. Jika tidak dilakukan oleh petugas berwenang atau tidak sesuai prosedur hukum, tindakan tersebut dapat dikategorikan melanggar kewenangan. Pasal 265 ayat (3) UU LLAJ mengatur bahwa hanya petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor, yang mencakup kewenangan untuk menghentikan kendaraan, meminta keterangan dari pengemudi, serta melakukan tindakan lain yang sah menurut hukum, sepanjang tindakan tersebut dilakukan secara bertanggung jawab. Ketentuan dalam pasal ini secara tegas menyatakan bahwa kewenangan untuk melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan pada prinsipnya berada di tangan petugas Polri. Hal ini mengimplikasikan bahwa instansi lain seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), maupun pejabat daerah lainnya tidak memiliki kewenangan mandiri untuk melakukan pemeriksaan, kecuali dalam kerangka kegiatan terpadu sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (2) dan ayat (3).
Lebih lanjut, Pasal 266 ayat (4) secara eksplisit menegaskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) hanya dapat melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan apabila didampingi oleh petugas Polri. Dengan demikian, keberadaan petugas Polri menjadi syarat mutlak bagi legalitas tindakan pemeriksaan oleh PPNS, untuk menjamin bahwa kewenangan tersebut tidak dijalankan secara sewenang-wenang dan tetap berada dalam koridor hukum yang sah. Pasal 265 ayat (1) juga mengatur bahwa pemeriksaan yang dilakukan harus berdasarkan alasan yang sah, bukan diskriminatif.
Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur petugas yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala atau insidental atas dasar operasi kepolisian dan/atau penanggulangan kejahatan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas. Hal ini berarti setiap razia harus memiliki surat perintah resmi. Tanpa surat perintah, pemeriksaan bisa dianggap ilegal.
Apabila suatu pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor di jalan dilakukan dengan cara yang intimidatif atau tanpa didasarkan pada kewenangan yang sah, maka tindakan tersebut tidak semata-mata bertentangan dengan ketentuan Pasal 265 dan Pasal 266 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum yang lebih serius, antara lain:
a. Pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara untuk bebas bergerak, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Pemenuhan unsur tindak pidana perampasan kemerdekaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 333 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP);
c. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat, yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 421 KUHP.
Perspektif Teori Hukum Pidana
Tindakan pejabat negara yang menggunakan kekuasaannya untuk membatasi hak-hak warga negara wajib diuji melalui tiga asas fundamental dalam negara hukum, yakni asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Ketiga asas ini tidak hanya merupakan prinsip administratif, tetapi juga bagian integral dari perlindungan hukum terhadap hak konstitusional warga negara, terutama ketika berhadapan dengan tindakan aparatur negara yang represif atau berpotensi menyalahgunakan kewenangan.
Dalam perspektif teori legalitas yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, hukum merupakan norma tertinggi (grundnorm) yang mengikat seluruh tindakan pejabat negara. Artinya, tidak ada jabatan, otoritas, atau kepentingan politik yang dapat membenarkan tindakan yang tidak memiliki dasar hukum yang sah. Setiap bentuk kekuasaan pemerintahan hanya sah apabila dijalankan dalam kerangka norma hukum yang berlaku. Kelsen menegaskan bahwa struktur negara hukum menuntut setiap bentuk tindakan administratif maupun represif dari pejabat publik tunduk pada prinsip normative hierarchy, di mana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan seluruh tindakan pejabat harus sesuai dengan norma hukum yang ada.
Dalam praktiknya, jabatan publik bukanlah sumber kekebalan hukum, melainkan merupakan amanah konstitusional yang diperketat oleh prinsip pertanggungjawaban hukum. Hal ini sejalan dengan teori tindak pidana jabatan (ambtelijke delicten) dalam hukum pidana, yang menyatakan bahwa terdapat bentuk-bentuk kejahatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memegang jabatan publik, dan perbuatannya menjadi tindak pidana justru karena dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pejabat.
Salah satu manifestasi dari ambtelijke delicten adalah penyalahgunaan kekuasaan atau yang secara yuridis dikenal sebagai abuse of power. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 421 KUHP, yang mengancam pejabat dengan pidana penjara apabila menggunakan kewenangannya secara menyimpang untuk memaksa warga negara melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu. Penyalahgunaan kewenangan tersebut menjadi delik karena bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi telah melanggar hak fundamental warga negara dan menyalahi prinsip negara hukum (rechtstaat).
Selain itu, dalam konteks perlindungan hak individu, asas proporsionalitas juga memegang peran penting dalam membatasi intervensi kekuasaan negara. Asas ini menuntut agar setiap pembatasan terhadap hak warga negara dilakukan secara seimbang antara tujuan yang ingin dicapai dan dampak yang ditimbulkan. Pemeriksaan yang sewenang-wenang, apalagi disertai dengan paksaan atau intimidasi, merupakan pelanggaran terhadap prinsip tersebut dan dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang melanggar hukum.
Dengan demikian, tindakan pejabat publik yang membatasi kebebasan bergerak warga negara, tanpa dasar hukum yang jelas, tanpa prosedur yang sah, dan disertai pemaksaan, tidak hanya mencederai prinsip legalitas, tetapi juga berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Negara hukum tidak memberi ruang bagi kekuasaan yang bekerja di luar hukum; justru hukumlah yang menjadi batas dan pengendali kekuasaan.
Kesimpulan: Perlu Penegakan Hukum yang Tegas
Razia kendaraan berdasarkan pelat nomor daerah tanpa dasar hukum yang eksplisit dan prosedural bukan sekadar polemik administratif, melainkan berpotensi menjadi tindak pidana yang patut diuji secara hukum. Oleh karena itu, jika ditemukan fakta bahwa:
a. Instruksi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah;
b. Warga Aceh diperlakukan secara diskriminatif dan kehilangan hak mobilitas;
c. Tindakan dilakukan oleh pejabat dengan kewenangan formal,
Maka tindakan tersebut dapat memenuhi unsur Pasal 421 dan Pasal 333 KUHP, dan seharusnya ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum secara objektif dan independen. Negara hukum bukan hanya slogan. Ia menuntut bahwa setiap kekuasaan dijalankan dalam koridor konstitusi dan hukum. Apalagi dalam situasi sosial yang sensitif seperti hubungan antar daerah dan perlakuan warga lintas provinsi, kebijakan yang tidak berlandaskan hukum justru dapat memperkeruh integrasi nasional. Penegakan hukum dalam kasus ini bukan hanya soal individu, tetapi tentang menjaga batas kekuasaan dalam sistem hukum yang demokratis dan beradab.
Penulis Opini: Andi Rachmad (Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas)